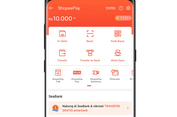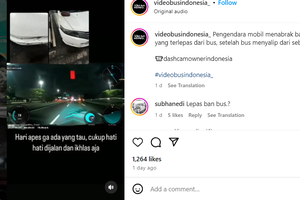Mendaur Ulang Residu Jokowinomic

TIDAK bisa dipungkiri, Jokowi-JK tergolong kurang beruntung karena memulai pemerintahan di saat perekonomian global sedang meradang.
Bagaimana tidak, pada akhir Oktober 2014 atau sepekan setelah Jokowi-JK dilantik, Bank Sentral AS (The Fed) mengakhiri program quantitative easing (QE) atau pembelian aset obligasi untuk memompakan likuiditas ke pasar.
Keputusan AS menghentikan QE membuat pasar finansial, khususnya pasar saham dan pasar valas, di seluruh dunia bergejolak. Setelah dihentikan, QE yang dimulai pada tahun 2008 untuk memitigasi krisis moneter akibat kredit macet properti berkualitas rendah (subprime mortgage) di AS, memicu kembalinya dana asing di seluruh dunia (suden reversal) , termasuk Indonesia, ke Negeri Paman Sam.
Dampak penghentian program QE memang tidak langsung terasa, meski The Fed sudah mengurangi pembelian obligasi (tapering off) sejak Januari 2014. Walhasil, ekonomi Indonesia pada 2014 masih tumbuh 5,02 persen.
Baca juga: Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa
Namun pada 2015, pertumbuhan ekonomi nasional terpangkas hingga menjadi 4,88 persen. Rupiah dan pasar saham domestik mengalami turbulensi. Tidak bisa tidak, di dalam negeri pun suku bunga acuan harus dipatok tinggi.
Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi 4,88 persen pada 2015 digadang-gadang sebagai prestasi yang lumayan hebat. Dengan pencapaian itu, Indonesia tercatat sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi nomor tiga di Asia Pasifik.
Ekonomi Indonesia hanya kalah oleh India dan Tiongkok yang masing-masing tumbuh 7,3 persen dan 6,8 persen.
Tentu sangat bisa dipahami mengapa Indonesia ada di posisi tersebut. Dengan jumlah penduduk yang besar, kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi andalan penopang pertumbuhan ekonomi.
Dalam logika tersebut, wajar mengapa Indonesia ada di bawah China dan India, karena jumlah penduduk Indonesia juga ada di bawah kedua negara tersebut. Dalam bahasa yang lain bisa dikatakan bahwa pertumbuhan yang didapat di tahun 2014 adalah pertumbuhan alami yang tak terlalu jauh dengan yang didapat beberapa tahun setelahnya.
Dengan raihan itu, pemerintah masih dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi sulit, pemerintah juga dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun selanjutnya.
Buktinya, pada 2016, perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi ke level 5,02 persen. Salah satu kunci yang dimainkan pemerintahan Jokowi-JK adalah memacu pertumbuhan ekonomi di tengah masa sulit dengan menjaga APBN tetap kredibel, efektif, dan terkelola dengan baik (manageable).
Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK: Era Baru Ekonomi Indonesia?
Kendati kualitas penyerapan anggaran belum sesuai harapan, pemerintah berhasil membangun postur APBN dengan resiliensi atau elastisitas yang cukup tinggi. Setidaknya, demikianlah narasi ekonomi yang digadang-gadang kala itu.
Disadari atau tidak, APBN 2015 dan 2016 – begitu pula APBN 2017— sejatinya menghadapi risiko guncangan fiskal yang cukup berat akibat perlambatan ekonomi global yang menyebabkan penerimaan negara dari sektor perpajakan meleset dari target.
Oleh karena itu, agenda pengetatan (auterity) menjelma ke dalam instilah "belanja yang efektif dan efisien" dan pemerintah digadang-gadang berhasil menjaga APBN tetap memiliki kemampuan beradaptasi dan tak goyah dalam situasi sulit.
Namun di sisi lain, angka raihan pajak ternyata tak berada dalam posisi yang supportif. Dua tahun pertama, penerimaan negara dari pajak hanya bermain di angka 81-82 persen. Lalu di tahun 2017, angkanya naik ke 92 persen karena adanya suntikan penerimaan dari kebijakan tax amnesty.
Tak dapat dipungkiri memang, ada…
-
![]()
Kuartal III 2018, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17 Persen
-
![]()
Ketahanan Ekonomi Indonesia Dipakai Jadi Contoh di Pertemuan IMF-Bank Dunia
-
![]()
Sri Mulyani Senang dengan Hasil Survei Ekonomi Indonesia Versi OECD
-
![]()
OECD: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Tetap Solid
-
![]()
Faisal Basri: Ekonomi Indonesia Tidak Dikuasai Asing